Kemarin
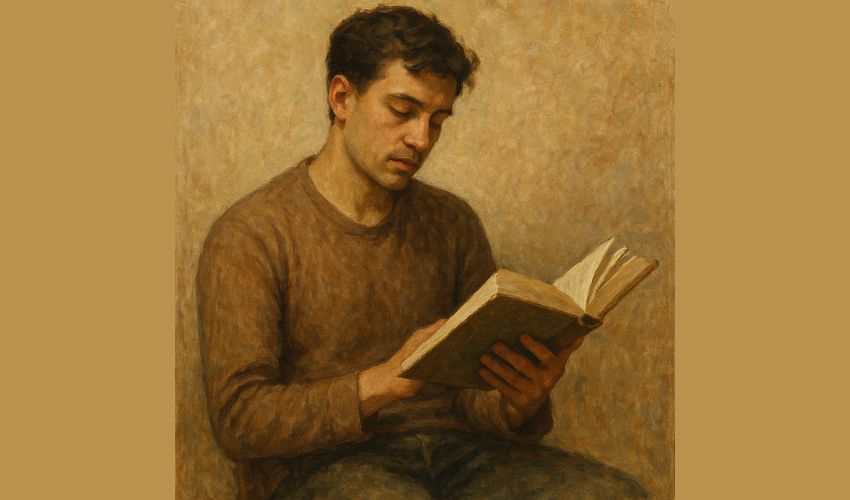
Kemarin adalah hari yang biasa. Tidak ada hujan, tidak ada pesta. Hanya desir angin yang menyentuh pohon cemara di ladang belakang rumah kami. Matahari tenggelam seperti biasa, lamban, merah, dan malu-malu. Tetapi siapa yang menyangka, dari satu hari yang tampak biasa, hidup bisa terbelah seperti kayu lapuk dipukul kampak?
Ayah duduk di kursi goyangnya, menghadap jendela yang selalu ia buka setiap pagi. Ia menyukai sinar pagi seperti seorang petani mencintai ladangnya. Tapi kemarin, ia membuka jendela dengan enggan. Tangannya gemetar, dan napasnya terdengar seperti rantai yang beradu di sumur tua.
“Langit hari ini tidak biru,” katanya padaku, tanpa menoleh.
Aku mengangguk, meskipun aku tahu langit justru sangat biru. Tidak ada awan. Tidak ada tanda hujan. Tapi di matanya, langit telah redup sejak lama.
“Kenapa, Ayah?” tanyaku sambil menuangkan teh ke cangkirnya.
Ia tak menjawab. Ia hanya memandang seekor burung pipit yang bertengger di pagar. Lalu matanya memejam, seperti sedang mencoba mendengar sesuatu yang tidak terdengar oleh manusia.
**
Kemarin juga hari di mana surat itu datang. Sebuah amplop cokelat, dibawa oleh lelaki berseragam yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Ia tidak tersenyum, bahkan tidak mengangguk. Ia hanya berkata, “Untuk Tuan Ivan.” Dan pergi, seperti utusan dari takdir.
Aku mengambil surat itu dan menyerahkannya pada Ayah. Ia menatap amplop itu lama sekali, seolah bisa membaca isinya dari luar. Kemudian ia berkata pelan, “Akhirnya.”
Surat itu dari Moskow. Materai merah dan cap resmi tergambar di sudutnya. Tulisannya tegas dan rapi. Aku membacanya setelah Ayah memberiku isyarat. Di dalamnya hanya ada satu paragraf:
“Pemerintah memutuskan untuk mengambil kembali tanah ladang seluas lima hektar yang diberikan pada tahun 1983, demi kepentingan industri dan pembangunan jalur kereta api baru. Penduduk diminta segera mengosongkan wilayah tersebut dalam waktu 30 hari sejak surat ini diterima. Kompensasi akan diberikan sesuai peraturan.”
**
Aku mendongak, dan mata Ayah masih menatap burung pipit itu. “Kamu tahu, ladang itu bukan hanya tanah. Di sana ada ibu kalian.”
Aku menunduk. Aku tahu maksudnya. Di ujung ladang, di bawah pohon apel yang kini sudah renta, terbaring tubuh Ibu. Ia dikuburkan di sana atas permintaannya sendiri. Ia ingin dekat dengan tanah yang ia bajak setiap pagi.
Kemarin juga adalah hari di mana adikku, Pyotr, kembali dari kota. Ia datang dengan mobil hitam mengilat, mengenakan jas mahal, dan bau parfum menyengat.
“Ayah, sudah waktunya kalian menyerah pada zaman. Ladang itu tak menghasilkan apa-apa. Ambil saja uangnya. Kita bisa hidup di kota, nyaman. Aku bisa menyewa apartemen untuk kalian,” katanya.
Ayah hanya menghela napas. Ia tidak membantah. Tidak juga menyetujui. Hanya diam, seperti orang yang menunggu ajal dengan sabar.
“Ayah tidak mengerti ekonomi,” kata Pyotr padaku kemudian. “Pemerintah pasti akan mengambil tanah itu, suka atau tidak. Setidaknya, kita ambil kompensasinya.”
Aku tidak menjawab. Aku tahu Pyotr tidak jahat. Ia hanya terbentuk dari dunia yang terlalu cepat dan tak sempat mengenal aroma jerami.
Kemarin malam, aku menemukan Ayah di ladang. Ia duduk di atas tanah yang basah oleh embun. Di sampingnya ada cangkul tua. Tangannya memegang segenggam tanah dan meletakkannya di dada.
“Tanah ini punya suara, Misha,” katanya. “Kalau kau diam cukup lama, kau akan mendengarnya. Mereka bilang tanah ini hanya sebidang properti. Tapi tanah ini lebih tahu tentang kita daripada pemerintah mana pun.”
**









