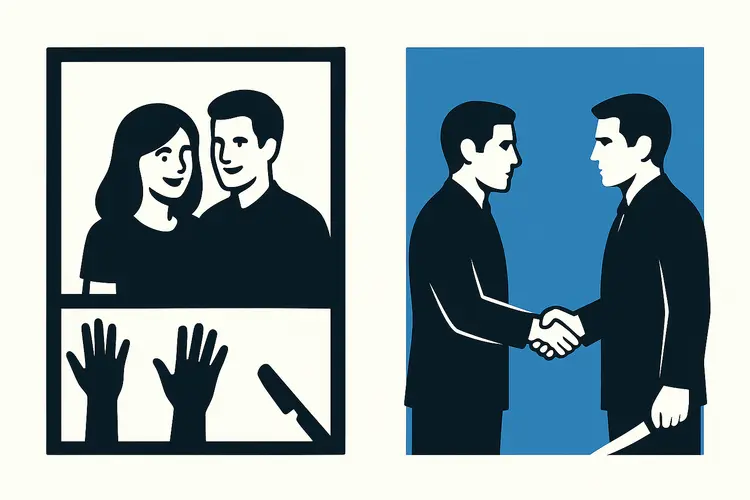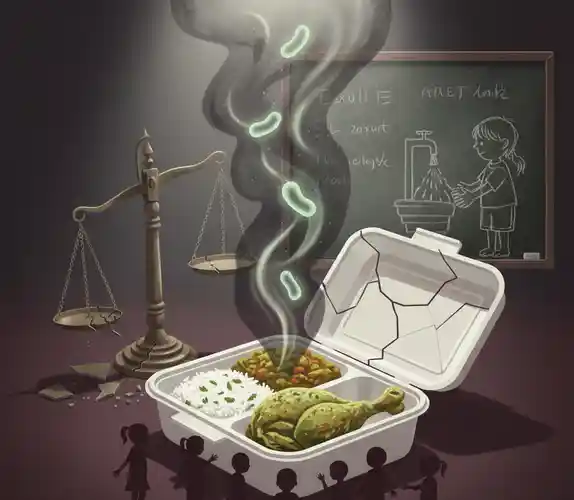Upacara Pengabuan Seorang Patung
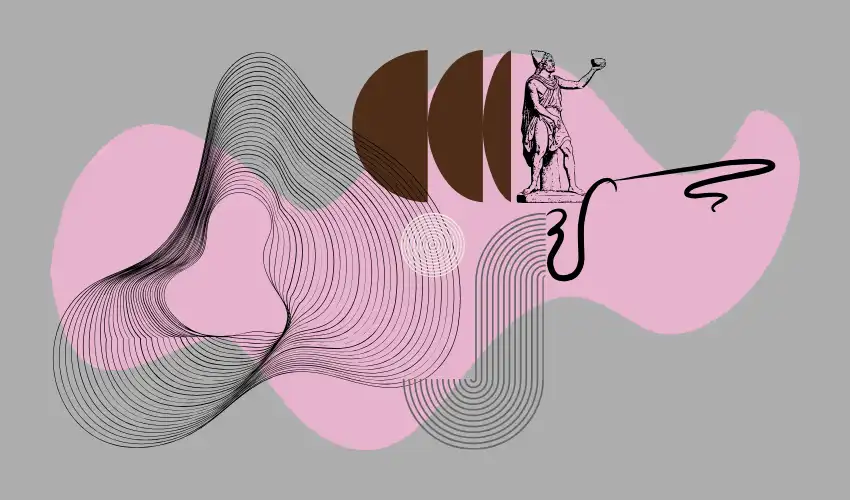
Ada satu pagi yang tidak pernah benar-benar selesai dipagi-hari-kan bangsa ini. Matahari muncul agak ragu—seperti seorang petugas arsip yang menemukan berkas lama, penuh noda kopi dan bercak minyak, lalu bertanya apakah dokumen itu masih layak didaftarkan sebagai sejarah. Di halaman depan negara, di antara deretan gedung yang selalu lapar subsidi cat putih, berlangsung sebuah upacara ganjil: upacara pengangkatan seorang pahlawan yang sudah lama menjadi patung. Patung yang konon pernah hidup, pernah menjadi bapak, pernah menjadi algojo, pernah menjadi penyayang, pernah menjadi penentu harga beras dan sekaligus harga kesunyian.
Upacara itu, tentu saja, penuh musik mars yang kedengarannya seperti nostalgia pada era ketika semua orang dipaksa berbaris rapi agar tampak seolah bahagia.
Tetapi siapa peduli bentuk asli dari kebahagiaan, selama ia difoto dalam resolusi cukup tinggi?
*****
Bangsa ini memang memiliki kecenderungan yang aneh: kita lebih percaya pada patung daripada manusia. Manusia cenderung berubah—hari ini jujur, besok bisa bergosip. Patung tidak demikian; ia keras, tegar, dan tidak membantah, meski para burung memperlakukannya seperti toilet umum. Patung adalah cita-cita kita tentang keteguhan, sekaligus alasan untuk menghindari kenyataan bahwa keteguhan itu sering kali mengeras karena kesedihan yang tak pernah dibereskan.
Maka ketika ada gagasan—atau gumaman, atau desakan samar-samar dari lorong politik yang kita pura-pura tak ingin tahu—bahwa seseorang bernama Soeharto diusulkan kembali sebagai pahlawan, bangsa ini pun tidak terkejut. Kita hanya menguap pelan sambil menanyakan satu hal sederhana:
“Patung lagi? Yang itu? Sudah dicat ulang?”
Untuk mengangkat seorang pahlawan, tentu kita harus mengabaikan sebagian sejarah. Tetapi bukan bangsa ini namanya kalau tidak ahli mengabaikan kenyataan, terutama jika kenyataan itu berpotensi merusak suasana perayaan. Kita lupa bahwa sejarah bukan seperti kue lapis: bisa kita makan bagian manisnya saja, kita buang yang hambar atau terlalu gurih.
Tidak. Sejarah adalah tubuh—tidak bisa dipotong tanpa meninggalkan darah.
*******
Namun, apa yang lebih menarik daripada keputusan itu sendiri adalah kenikmatan simbolik yang menyertai prosesnya. Kita menyaksikan bagaimana “pahlawan” di negeri ini sering kali merupakan sebuah proyek estetika, bukan etika. Sebuah panggung. Sebuah mural yang bisa ditimpa ulang. Sebuah puisi yang dipaksa berima.
Soeharto dalam imajinasi sebagian orang adalah leluhur yang sabar—seorang petani tua yang duduk di kursi bambu, mengawasi sawah, dan sesekali menegur siapa pun yang mencoba menaikkan harga pupuk. Tetapi dalam imajinasi sebagian lainnya, ia adalah raksasa yang tumbuh dari tanah vulkanik: setiap langkahnya menggetarkan bumi, setiap perintahnya adalah gempa, dan setiap senyumnya mengandung sedikit getar horor yang tak bisa dihapus dengan program TVRI.
Dua imajinasi itu saling menelan, saling memamah, seperti dua ular yang menggigit ekor satu sama lain. Dan dari putaran itu, muncullah sebuah tanya yang dipelihara negara: dalam sebuah bangsa yang amnesia adalah kemampuan unggulan, siapa yang menentukan apakah seseorang layak menjadi pahlawan?
*****
Para perumus gelar itu—mereka yang duduk di kursi empuk sambil memeriksa riwayat hidup seseorang seperti memeriksa nilai rapor anak tetangga—sering lupa bahwa pahlawan tidak pernah lahir dari rapat. Pahlawan, kalau pun ada, lahir dari keretakan, dari poros sejarah yang terbelah, dari rasa sakit kolektif yang terlalu besar untuk disembunyikan di balik karangan bunga.
Tapi, tentu saja, kita bukan sedang membicarakan pahlawan. Kita sedang membicarakan pengangkatan pahlawan, yakni sebuah ritual yang lebih dekat dengan dunia panggung daripada dunia moral. Pengangkatan pahlawan adalah seni instalasi: kita menempatkan figur di sebuah podium tinggi, lalu kita pasang lampu, kita beri latar musik, kita cetak poster, dan kita minta publik bertepuk tangan. Tepuk tangan itu sendiri tidak penting. Yang penting adalah bahwa ada bunyi.
Sebagian bangsa hidup dari kerja keras. Kita hidup dari efek suara.
*******
Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan adalah sebuah eksperimen optik yang menarik. Ia menguji refleks bangsa ini: apakah kita akan menunduk, menghindari tatapannya, atau justru berdiri di depan patung itu sambil berkata, “Ah, mungkin selama ini kita yang salah baca sejarah.”
Sebab bangsa ini punya kebiasaan: ketika bingung menghadapi kenangan pahit, kita akan mengarang dongeng yang lebih manis. Kita percaya bahwa cukup dengan menaburkan sedikit gula pada kepahitan, sejarah akan berubah rasa.
Padahal sejarah adalah kopi tubruk: pahitnya bukan pilihan, melainkan sifat dasar.
Lalu bagaimana dengan mereka yang menganggapnya sebagai bapak pembangunan? Ah, istilah yang selalu berhasil membuat kita lupa bahwa pembangunan adalah kata yang indah untuk mengganti kata yang lebih jujur: penggusuran. Membawa bangsa maju memang terdengar heroik, sampai kita sadar bahwa sebagian kemajuan itu dibangun dari pondasi yang terbuat dari diam paksa.
Diam, dalam banyak hal, adalah mata uang paling stabil pada masa itu.
Namun siapa tahu, mungkin bangsa ini rindu pada stabilitas. Rindu pada masa di mana harga dipatok oleh tangan yang tak terlihat namun terasa. Rindu pada malam-malam yang sunyi, bukan karena damai, tapi karena semua orang tahu bahwa suara salah tempat bisa membuat esok tidak datang. Barangkali manusia memang sering merindukan trauma, terutama ketika trauma itu pernah menyajikan nasi di meja makan.
******
Menyaksikan kembali perdebatan soal pahlawan itu, saya teringat pada kebiasaan masyarakat dalam upacara adat beberapa daerah. Ada tradisi membakar boneka atau patung sebagai simbol pelepasan masa lalu. Menariknya, kita melakukan kebalikannya: kita membangkitkan boneka itu, meniupkan kembali napas simbolik ke dalam tubuh kayunya, dan berharap ia berjalan menuju masa depan.
Tetapi patung tidak pernah bisa berjalan. Ia hanya bisa ditarik.
Dan ketika sebuah bangsa menarik patung sambil berkata “lihat, ini pahlawan kami,” terkadang yang terjadi bukan penciptaan teladan baru, melainkan pengabuan nalar secara massal.
Upacara itu pun berubah menjadi prosesi religius baru: liturgi nostalgia.
*******
Namun esai budaya tidak pernah bertugas menghakimi; ia hanya bertugas menyentil. Maka biarlah kita mengupas peristiwa ini bukan sebagai perkara politik, melainkan sebagai gejala budaya: bangsa ini takut pada kekosongan. Kita tidak suka ruang tanpa figur. Kita selalu perlu seseorang untuk ditaruh di panggung tengah, agar sorotan lampu bisa diarahkan dengan jelas. Entah itu presiden, pahlawan nasional, artis TikTok, atau bahkan patung yang telah lama kehilangan warna aslinya.
Itulah sebabnya kita begitu mudah memaafkan—dan lebih mudah lagi melupakan. Kita ingin memiliki pahlawan yang tidak merepotkan: pahlawan yang tidak menuntut kita mengingat luka.
Pahlawan yang ideal, menurut budaya kita, adalah pahlawan yang tidak mengingatkan kita pada apa pun. Bukankah itu ironis?
*******
Soeharto sebagai pahlawan adalah eksperimen psikologi massal: seberapa besar kapasitas bangsa ini untuk menerima paradoks? Seberapa lentur ingatan kita? Dan seberapa jauh kita bisa memutar jam sejarah tanpa membuat jarumnya patah?
Di banyak negara, pahlawan adalah mimbar moral. Di sini, pahlawan adalah cermin retak. Kita melihat wajah sendiri di dalamnya, tetapi wajah itu terbelah-belah. Ada bagian yang tersenyum penuh penghargaan, ada yang meringis, ada yang menahan muntah, dan ada yang sama sekali tidak mengenali siapa yang dilihatnya.
Bangsa ini, pada akhirnya, bukan sedang menilai Soeharto. Bangsa ini sedang menilai dirinya sendiri.
******
Lalu apakah pengangkatan itu akan terjadi? Kita tak tahu. Kita bukan peramal. Kita hanya penonton—penonton dalam teater yang tiketnya dibagikan gratis sejak kita lahir sebagai warga negara. Yang jelas, upacara simbolik semacam ini akan terus berulang, sebab kita tidak pernah benar-benar tuntas dengan masa lalu.
Masa lalu, seperti asap dupa di kuil tua, meresap ke pakaian; betapapun kerasnya kita cuci, aromanya tetap tinggal.
Maka jika nanti Soeharto akhirnya diangkat sebagai pahlawan, itu bukan hanya keputusan politik. Itu adalah pernyataan budaya:
Bahwa bangsa ini lebih suka mengangkat masa lalu daripada memikul masa depan.
Bahwa kita masih percaya pada wajah-wajah yang telah membatu.
Bahwa kita memilih keamanan simbolik daripada kejujuran sejarah.
Bahwa kita, pada akhirnya, adalah masyarakat yang jatuh cinta pada patung—bukan karena patung itu benar, melainkan karena patung tidak pernah membantah.
Dan seorang pahlawan yang tidak pernah membantah adalah pahlawan yang paling mudah dirawat.
********
Barangkali suatu hari nanti, generasi mendatang akan membuka arsip ini dan bertanya: “Mengapa orang-orang pada masa itu begitu sibuk dengan gelar pahlawan?” Lalu mungkin mereka akan tertawa, atau menangis, atau heran mengapa kita begitu canggung dalam berhadapan dengan sejarah.
Tetapi sebelum hari itu tiba, kita masih harus menjalani upacara demi upacara, merayakan patung demi patung, sambil berharap bahwa suatu saat kepala kita tidak lagi dipenuhi oleh suara-suara mars yang terjebak di kaset kusut masa lalu.
Sebab bangsa ini, entah karena ketidaksengajaan atau memang takdir, selalu memutar ulang kaset itu. Mungkin karena kita percaya bahwa setiap lagu lama bisa terdengar lebih indah asalkan volume disesuaikan dan bass dinaikkan sedikit.
Namun sejarah bukan karaoke. Ia tidak bisa di-remix sesuka hati.
*********
Dan pagi itu, ketika upacara pengangkatan pahlawan berlangsung, saya melihat seorang anak kecil bertanya pada ayahnya, “Ayah, siapa itu?” Sang ayah diam lama, seperti menelan debu sejarah yang tiba-tiba melayang dari podium.
Akhirnya ia menjawab dengan suara pelan:
“Dia adalah seseorang yang dulu pernah menentukan cara kita hidup. Dan sekarang mereka ingin menentukan cara kita mengingat.”
Dan di situlah inti persoalannya. Pengangkatan pahlawan bukan soal sejarah yang telah terjadi, melainkan sejarah yang ingin dipaksa terjadi kembali. Sebuah upaya untuk mengarahkan ingatan publik seperti mengarahkan cahaya panggung.
Tetapi cahaya panggung hanya menyinari permukaan patung. Tidak pernah sampai ke rongga gelap dalam dada kita.
Rongga tempat sejarah sejati bersembunyi.
********
Maka esai ini hanya ingin mengingatkan: bahwa bangsa yang sibuk mengangkat patung dari masa lalu sering lupa membangun manusia di masa depan.
Dan barangkali, sebelum kita mengangkat pahlawan baru—atau pahlawan lama yang dilabeli baru—kita perlu terlebih dulu belajar menjadi warga yang mampu memikul masa lalu apa adanya, tanpa kosmetik, tanpa aransemen musik, tanpa panggung.
Sebab hanya bangsa yang berani menatap bayangannya sendiri yang pantas memiliki pahlawan.
Bukan bangsa yang terus-menerus menggambar patung untuk menutupi rasa takut pada cermin.
Editor: Andi Surianto