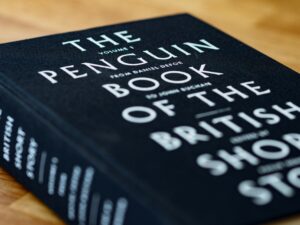Sedikit Membaca, Sedikit Berpikir

Indonesia sedang menghadapi sebuah paradoks intelektual yang menggelisahkan. Di satu sisi, ruang publik kita—terutama media sosial—sangat bising. Jari-jemari warganet begitu lincah menari di atas layar, memproduksi komentar, perdebatan, dan opini tiada henti. Namun, di balik riuh rendah digital tersebut, terdapat kesunyian yang memilukan di ruang-ruang literasi. Kita menjadi bangsa yang “cerewet” menyampaikan pendapat, namun gagap dalam mencerna informasi.
Fenomena ini bukan sekadar asumsi, melainkan realitas yang terpotret jelas. Laporan Batam Pos (30 Juli 2025) menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya bertengger di angka 0,001%, jauh tertinggal dari standar global. Di lingkungan akademis pun, situasinya tak kalah pelik. Survei di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2025) mencatat hanya 38% mahasiswa yang aktif membaca, dengan durasi mayoritas kurang dari satu jam per hari.1 Jika kaum intelektual muda saja enggan bergulat dengan teks, lantas bagaimana kita bisa berharap pada ketajaman nalar masyarakat umum?
Dari Deep Reading ke Shallow Skimming
Masalah utamanya bukan sekadar “malas membaca”, melainkan pergeseran fundamental dalam cara kita mengonsumsi informasi. Situs pemerintah Lamongan (2025) menyoroti bahwa Generasi Z kini lebih dominan mengonsumsi konten digital singkat daripada teks panjang. Ini adalah gejala matinya Deep Reading (membaca mendalam).
Ketika kita membaca buku, otak dilatih untuk fokus, menyusun logika linier, dan merenung. Sebaliknya, ketika kita berselancar di media sosial, otak terbiasa melakukan skimming (membaca cepat) dan melompat-lompat. Akibatnya, seperti dilansir oleh Komdigi, anak muda cenderung menyerap informasi instan tanpa filter analisis. Kita sedang membesarkan generasi yang memiliki “obesitas informasi” namun mengalami “busung lapar pengetahuan”.
Jebakan Ilusi Literasi
Dampak dari hilangnya budaya Deep Reading ini menciptakan apa yang saya sebut sebagai “Ilusi Literasi”. Kita merasa sudah membaca, padahal hanya mengeja.
Hal ini terbukti secara empiris melalui penelitian Hasanah dkk. (2022) di SMAN 12 Rejang Lebong. Data menunjukkan sebuah anomali menarik: skor kebiasaan membaca siswa tergolong tinggi (rata-rata 74,37), namun kemampuan berpikir kritis mereka anjlok di angka 62,57.2 Mengapa ketimpangan ini terjadi? Jawabannya terletak pada kualitas bacaan. Siswa mungkin sering membaca (status media sosial, pesan singkat, atau artikel ringan), namun aktivitas tersebut tidak cukup kompleks untuk menstimulasi neokorteks otak dalam melakukan analisis evaluatif. Tanpa bacaan yang “bergizi”, otot kritis otak menjadi tumpul.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bangka Belitung (2019) juga mengonfirmasi bahwa rendahnya mutu bacaan berkorelasi lurus dengan merosotnya mutu pendidikan. Kita melahirkan lulusan yang mampu menghafal, namun lumpuh ketika diminta memecahkan masalah kompleks atau membedakan fakta dan hoaks.
Akar Masalah Sistemik
Tentu, menyalahkan individu semata adalah tindakan yang naif. Sampoerna Foundation (2024) dan Kalla Institute memberikan konteks bahwa krisis ini bersifat sistemik. Hanya 10% penduduk yang tercatat rajin membaca buku secara konsisten. Faktor dominasi gawai sejak usia dini dan akses bahan bacaan yang tidak merata menciptakan “tembok penghalang” bagi tumbuh kembangnya budaya berpikir.
Kita sedang menyaksikan sebuah kesenjangan berbahaya: akses internet merata, namun akses terhadap literasi berkualitas timpang. Akibatnya, generasi muda tumbuh dengan kemampuan teknis yang canggih, namun dengan fondasi kognitif yang rapuh.
Menyalakan Kembali Api Nalar
Rendahnya minat baca bukan lagi sekadar masalah hobi atau preferensi, melainkan ancaman eksistensial bagi masa depan bangsa. Data-data dari tahun 2024 dan 2025 di atas adalah sinyal bahaya (SOS) bagi dunia pendidikan kita. Sedikit membaca terbukti secara ilmiah menghasilkan sedikit berpikir.
Untuk memenangkan masa depan, intervensi pendidikan tidak boleh lagi bersifat seremonial belaka. Kita tidak butuh sekadar “Pojok Baca” yang berdebu. Kita membutuhkan kurikulum yang memaksa siswa untuk kembali melakukan Deep Reading—membaca teks panjang, membedah argumen, dan menuliskan sintesis. Kita harus mengubah mentalitas dari “membaca untuk tahu” menjadi “membaca untuk berpikir”. Hanya dengan cara itulah, kita bisa mengubah generasi yang bising di media sosial menjadi generasi yang bijak dalam realitas, yang tidak hanya tajam lidahnya, tetapi juga tajam nalarnya.
Sumber Rujukan
- Sukci, L. B. P., & Fitriati, A. (2025). Reading Habits Among Students of Universitas Atma Jaya Yogyakarta. LATTE: A Journal of Language, Culture, and Technology ISSN 3063-0754, 3(1). https://doi.org/10.24002/lj.v3i1.11658 ↩︎
- Hasanah, R., Martina, F., & Afriani, Z. L. (2022). The Correlation Between Students’ Reading Habit and Critical Thinking Skills. JPT: Jurnal Pendidikan Tematik, 3(1). https://siducat.org/index.php/jpt/article/view/499 ↩︎