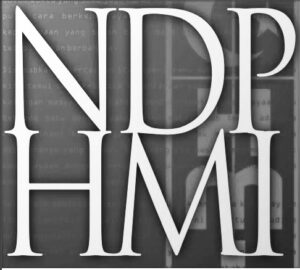Puasa Dopamin
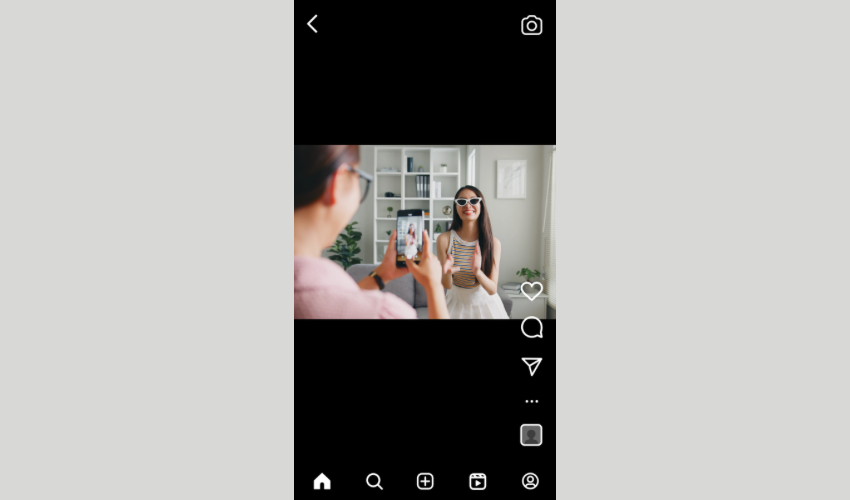
Sering kali kita tersadar di jam dua pagi dengan mata yang sudah perih dan tengkuk yang kaku, tapi jempol ini seolah menolak berhenti mengusap layar ponsel. Padahal, kita tahu persis besok pagi ada tumpukan pekerjaan, rapat penting, atau sekadar rutinitas harian yang menuntut kita bangun pagi. Otak rasanya sudah memohon untuk tidur. Tapi anehnya, tubuh kita menolak diajak kompromi.
“Ah, satu video lagi,” batin kita. Atau mungkin, “Coba baca komentar di thread ini sebentar.”
Niat awalnya biasanya sangat sederhana dan polos. Cuma mau mengecek ponsel lima menit sebelum benar-benar memejamkan mata. Namun, tahu-tahu lima menit itu menguap dan berubah wujud menjadi dua jam kehampaan. Saat akhirnya kita benar-benar mengunci layar dan mematikan lampu kamar, perasaan yang tersisa jarang sekali berupa kepuasan. Yang ada malah rasa sesak, bersalah, lelah yang aneh, dan kekosongan.
Kalau sudah di fase ini, refleks pertama kita sebagai manusia biasanya adalah merutuki diri sendiri. Kita merasa jadi makhluk paling tidak disiplin di muka bumi. Kita merasa kurang iman, pemalas, atau sekadar payah dalam mengatur waktu.
Berhenti menghakimi diri sendiri sekeras itu. Mari kita lihat realitasnya: Anda tidak lemah. Kita semua hanya sedang kalah bertarung.
Masalahnya, arena pertarungan ini dari awal memang tidak pernah dirancang untuk seimbang. Ketika kita membuka aplikasi media sosial—entah itu TikTok, Instagram, X, atau apa pun namanya—kita tidak sedang berhadapan dengan aplikasi biasa. Di balik layar kaca itu, ada ribuan insinyur paling brilian di Silicon Valley, disokong oleh superkomputer, dan digerakkan oleh algoritma kecerdasan buatan. Tujuan mereka cuma satu dan sangat spesifik: menyandera perhatian kita selama mungkin.
Dan tebak apa senjata utama mereka? Bukan kode pemrograman yang rumit, melainkan biologi di dalam kepala kita sendiri.
Mesin Slot di Dalam Saku Celana
Untuk paham kenapa kita susah sekali meletakkan ponsel, kita harus membicarakan satu zat kimia di otak yang bernama dopamin.
Selama ini, banyak yang salah kaprah menganggap dopamin sebagai “hormon kebahagiaan”. Mitosnya, kalau dopamin naik, kita jadi senang. Padahal, sains neurobiologi sudah lama membuktikan kalau cara kerjanya tidak begitu. Dopamin itu sebenarnya hormon motivasi. Dia adalah molekul yang membuat kita penasaran. Zat ini tidak disemprotkan oleh otak saat kita mendapatkan hadiah, melainkan saat kita sedang mengantisipasi hadiah tersebut.
Coba bayangkan suasana di sebuah kasino. Seseorang duduk di depan mesin slot, memasukkan koin, lalu menarik tuasnya. Roda bergambar mulai berputar cepat. Nah, pada detik-detik roda itu berputar, di situlah dopamin membanjiri otak. Ada ketidakpastian di sana. Pemainnya tidak tahu apakah dia akan menang besar (jackpot) atau malah zonk.
Dalam bahasa sains, ketidakpastian ini menciptakan apa yang disebut reward prediction error. Evolusi membuat otak manusia sangat sensitif terhadap kejutan. Kalau mesin slot itu selalu memberikan hadiah yang sama persis setiap kali ditarik, orang pasti cepat bosan. Tapi karena hasilnya acak, orang jadi ketagihan menarik tuasnya lagi dan lagi.
Sekarang, coba perhatikan desain aplikasi di ponsel kita. Saat kita menarik layar ke bawah untuk memperbarui linimasa (pull-to-refresh), sebenarnya kita sedang melakukan gerakan yang sama persis dengan menarik tuas mesin slot. Bedanya, mesin slot ini digital dan selalu ada di saku celana kita.
Gerakan jari itu memberi kita semacam ilusi kendali. Padahal, apa yang muncul setelah layar loading selesai sepenuhnya diatur oleh algoritma. Kita tidak pernah tahu apa yang akan disajikan. Bisa jadi foto teman lama yang baru menikah, berita kecelakaan yang bikin jantungan, meme kucing yang lucu, atau sekadar iklan sepatu. Karena kita tidak pernah tahu pasti apa yang menanti di bawah sana, otak kita terus memerintahkan: “Ayo, usap layarnya sekali lagi. Siapa tahu ada yang lebih seru.” Ini bukan lagi sekadar hiburan. Ini adalah perjudian kognitif.
Ilusi Mangkuk yang Tidak Pernah Kosong
Dulu, zaman sebelum internet secepat sekarang, teknologi hiburan punya “rem pakem” yang natural. Buku fisik punya halaman terakhir. Koran punya edisi harian yang habis dibaca dalam sejam. Acara televisi punya jam tayang yang akan ditutup dengan iklan atau lagu kebangsaan.
Jeda-jeda fisik ini sangat penting. Mereka bertindak sebagai sinyal bagi otak yang berkata: “Oke, kegiatan ini sudah selesai. Kamu mau lanjut kerja atau melakukan hal lain?”
Media sosial modern secara sadar dan sengaja menghancurkan rem tersebut melalui inovasi yang disebut infinite scroll (gulir tanpa batas). Dengan menghilangkan sistem halaman (seperti memencet tombol ‘Next’ atau ‘Halaman 2’ di blog zaman dulu), aplikasi menghilangkan semua gesekan yang bisa membuat kita berhenti berpikir. Layar akan terus menyuapi kita dengan konten baru tanpa ujung.
Secara psikologis, ini memicu apa yang disebut Efek Zeigarnik. Otak manusia itu punya kebiasaan benci melihat sesuatu yang belum selesai. Karena linimasa media sosial tidak pernah punya garis finis, otak kita tertipu dan menganggap aktivitas scrolling ini sebagai “pekerjaan yang belum beres”. Akibatnya, kita masuk ke dalam kondisi trans yang merusak. Kita kehilangan orientasi waktu.
Kondisi ini makin parah karena kita masuk ke fase defisit dopamin. Psikiater Dr. Anna Lembke pernah membuat analogi yang pas soal ini. Bayangkan sistem penghargaan di otak kita itu seperti papan jungkat-jungkit antara rasa senang dan rasa sakit. Saat kita terus-menerus menembaki otak dengan dopamin murahan dari media sosial, otak akan kelelahan. Untuk menjaga keseimbangan, otak akhirnya menekan sisi “sakit” lebih kuat.
Lalu apa dampaknya? Saat kita mematikan ponsel dan kembali ke dunia nyata, kita merasa gelisah. Perasaan kita jadi tidak karuan, cemas, gampang tersinggung, dan hampa. Dan tebak apa yang kita lakukan untuk menghilangkan rasa tidak nyaman itu? Tangan kita secara refleks merogoh saku lagi, membuka ponsel lagi. Lingkaran setannya terkunci rapat.
Epidemi Bosan dan Solusi Palsu
Pertanyaan selanjutnya: kenapa dari awal kita gampang banget terpancing membuka ponsel?
Banyak orang bilang ini karena kita kesepian. Ternyata, berbagai riset terbaru membuktikan sebaliknya. Alasan paling kuat yang memprediksi kecanduan gawai adalah kebosanan. Ya, sekadar rasa bosan.
Kita hidup di era di mana kita, entah sejak kapan, lupa caranya berdiam diri. Tiap kali ada waktu luang sedetik saja—entah itu menunggu lampu merah berubah hijau, antre kasir di minimarket, atau berdiri canggung di dalam lift—kita merasa tidak sanggup menahan keheningan. Ruang kosong itu terasa menyiksa, sehingga kita buru-buru melarikan diri ke dunia digital.
Sialnya, ini adalah jalan keluar yang palsu. Di dunia maya, yang kita konsumsi adalah realitas yang sudah diedit sedemikian rupa. Kita melihat pameran hidup orang lain yang sempurna: liburan ke luar negeri, pencapaian karier, rumah baru, atau wajah mulus berkat filter. Tanpa sadar, kita membandingkan kehidupan kita yang sedang berantakan ini dengan etalase kesempurnaan milik orang lain.
Bukannya rasa bosan hilang, pelarian ini justru memupuk rasa rendah diri, memicu depresi, dan menumbuhkan kecemasan. Otak purba kita menerjemahkan ketidaktahuan atas tren (FOMO) sebagai ancaman. Seolah-olah kalau kita tidak tahu gosip terbaru hari ini, kita akan dikucilkan dari peradaban.
Ongkos Biologis yang Sedang Kita Bayar
Coba lihat sekeliling kita. Merujuk pada data awal tahun 2025 lalu, ada lebih dari 143 juta orang Indonesia yang aktif di media sosial. Pemandangannya seragam di mana-mana: di warung kopi, di gerbong KRL yang berdesakan, sampai di meja makan keluarga. Semua orang menunduk. Wajah mereka disinari pendar kebiruan dari layar.
Kelompok usia produktif, terutama Gen Z, bisa menghabiskan empat sampai enam jam sehari murni hanya untuk scrolling. Belum lagi fenomena doomscrolling—kebiasaan mengonsumsi berita tragis dan negatif secara maraton yang bikin kita makin paranoid melihat masa depan.
Ini bukan lagi sekadar perkara membuang-buang waktu. Ada ongkos biologis yang sedang kita cicil setiap harinya. Paparan terus-menerus terhadap konten berkecepatan tinggi pelan-pelan mengubah struktur otak. Korteks prefrontal kita—bagian otak yang ngurusin kontrol diri, fokus, dan perencanaan—makin loyo. Efeknya? Kita jadi gampang lupa. Kita kehilangan kemampuan membaca teks yang agak panjang sedikit. Berpikir analitis jadi terasa melelahkan. Gejalanya pelan-pelan mirip orang yang mengidap ADHD.
Di sisi lain, amigdala kita (pusat emosi dan rasa takut di otak) justru makin sensitif. Kita jadi sumbu pendek, gampang marah cuma karena cuitan receh orang tidak dikenal di internet. Kurang tidur, stres, dan kelelahan mental ini sangat nyata.
Semua ini terjadi karena kita sedang hidup di tengah Attention Economy (Ekonomi Perhatian). Waktu dan fokus Anda adalah komoditas bernilai triliunan rupiah. Algoritma raksasa teknologi tidak punya kompas moral. Mereka tidak peduli konten itu bikin Anda pintar atau malah bikin Anda depresi. Selama konten itu memicu emosi yang kuat—entah itu marah, takut, atau iri hati—mereka akan terus menyuapkannya ke mata Anda.
Mantan desainer etis Google, Tristan Harris, bahkan menyebut ini sebagai human downgrading (penurunan kualitas manusia). Teknologi yang tadinya diciptakan untuk mempermudah hidup, pelan-pelan malah melucuti kapasitas dasar kita sebagai manusia yang berakal merdeka.
Merebut Kembali Kendali
Jadi, solusinya apa? Jelas bukan membuang smartphone ke sungai lalu pindah hidup di hutan. Itu tidak realistis. Di dunia modern ini, kita tetap butuh teknologi. Kuncinya adalah bagaimana kita merebut kembali kemudi atas pikiran kita sendiri.
Perlawanan ini bisa dimulai dari hal-hal yang terdengar sepele tapi lumayan radikal dampaknya.
Pertama, ciptakan “gesekan”. Musuh terbesar kita saat ini adalah kemudahan. Buatlah proses membuka media sosial jadi sedikit lebih menyebalkan. Matikan semua notifikasi yang tidak penting. Sisakan saja pesan langsung dari manusia beneran (seperti chat dari keluarga atau bos di kantor). Jangan biarkan algoritma yang mendikte kapan ponsel Anda harus bergetar mencari perhatian.
Bila perlu, pindahkan ikon Instagram atau TikTok dari layar utama. Masukkan ke dalam folder yang susah dicari, atau biasakan logout setiap kali selesai membuka aplikasi. Jeda beberapa detik yang dibutuhkan untuk mengetik password itu memberi ruang bagi otak untuk bertanya: “Tunggu dulu, aku beneran butuh buka ini, atau cuma lagi bosan aja?”
Kedua, jadwalkan puasa dopamin.
Tidak perlu ekstrem sampai harus puasa gawai berhari-hari. Cukup sediakan satu waktu spesifik—misalnya hari Minggu pagi sampai siang—di mana Anda benar-benar menjauh dari layar.
Apakah awalnya akan terasa menyiksa? Tentu saja. Tangan akan terasa gatal, perasaan jadi gelisah dan seperti ada yang kurang. Itu wajar, itu tanda otak sedang sakau dopamin. Tapi biarkan saja. Beri waktu bagi otak untuk melakukan kalibrasi ulang. Nanti, pelan-pelan kita akan bisa menikmati lagi hal-hal sederhana yang ritmenya lambat. Menikmati buku cetak, menyirami tanaman, atau sekadar duduk melihat langit sore tanpa merasa gatal ingin memotret dan mengunggahnya.
Terakhir, belajarlah untuk berteman lagi dengan kebosanan.
Bosan itu bukan musuh. Sepanjang sejarah umat manusia, rasa bosan adalah tempat lahirnya kreativitas. Ketika pikiran dibiarkan mengembara tanpa disuapi informasi yang berisik, di situlah ide-ide jernih biasanya muncul.
Kita saat ini sedang berada di tengah eksperimen sosial terbesar dalam sejarah peradaban, dan kitalah kelinci percobaannya. Algoritma di luar sana mungkin akan semakin canggih dan manipulatif. Tapi pada akhirnya, kendali atas tubuh dan jempol ini masih milik kita.
Perhatian, waktu, dan fokus Anda adalah aset paling berharga yang tidak bisa didaur ulang. Jangan berikan itu secara cuma-cuma kepada mesin yang tidak pernah peduli apakah Anda bahagia atau tidak. Hari ini, kalau Anda merasa bosan di tengah antrean atau saat menunggu lampu merah, cobalah tahan keinginan merogoh saku. Angkat kepala. Lihat sekeliling. Tarik napas. Dunia nyata memang kadang menjemukan dan tidak seindah filter di layar, tapi setidaknya, di situlah kita benar-benar hidup.