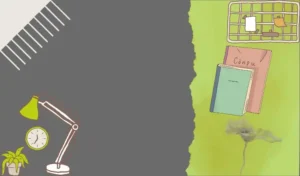Menggugat Nurani Umara dan Ulama
Ulama harusnya berada di tengah pasar yang pengap, gang-gang sempit nan becek, atau pematang sawah kering. Bukan malah mengisolasi diri di ketinggian lantai 40.

Rencana presiden Prabowo pada proyek pendirian gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) setinggi 40 lantai di pusat Jakarta bukanlah sekadar persoalan infrastruktur. Di atas lahan seluas 4.000 meter persegi, rencana tersebut tak ubahnya sebuah ambisi fisik yang hendak dipancang tinggi-tinggi. Sehingga, niatan itu—selain mesti terukur secara infrastruktur—mesti pula diuji secara moral, mengingat di akar rumput fondasi hidup rakyat justru sedang keropos dan babak belur.
Ingatan kita masih hangat, sewaktu mata kita tertumbuk paksa menyaksikan kontras yang melukai akal sehat: di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, seorang anak SD memilih mengakhiri hidupnya hanya karena kondisi ekonomi. Lalu, melalui mimbar, Prabowo mengeluarkan kalimat yang dimungkinkan akan kembali memproduksi musibah daftar tunggu: membangun sebuah menara megah yang akan menjulang ke langit.
Logika yang amat menyesakkan. Bagaimana mungkin kita bicara tentang kemegahan kantor para pemuka agama ketika BPJS untuk warga miskin diputus secara sepihak, atau saat luka bencana di Aceh belum sepenuhnya pulih? Ada disparitas yang mengerikan di sini. Prioritas negara seolah sedang mengalami disorientasi yang parah.
MUI adalah himpunan para ulama, pewaris nabi. Mustinya, merekalah yang paling peka membaca denyut nadi umat yang sedang kempis. Ulama seharusnya punya rasa malu dan tahu diri untuk mendahulukan perut rakyat dibandingkan sekadar simbol prestise berupa lift cepat dan dinding kaca yang mengilat.
Selama ini, berkantor di Masjid Istiqlal pun dakwah tetap berjalan. Fungsi ulama tidak membutuhkan pendingin ruangan terpusat atau karpet mewah di lantai puluhan. Ulama tidak butuh gedung pencakar langit untuk membicarakan urusan ketuhanan; mereka justru harus membumi untuk mengurusi kemanusiaan.
Maka, wajar jika muncul kecurigaan liar: apakah kemewahan ini adalah cara halus kekuasaan untuk menjinakkan daya kritis MUI? Apakah suara kritis mereka akan luruh dan melunak saat mereka mulai menikmati kenyamanan di puncak gedung?
Sebagai anak bugis, saya akrab dengan falsafah “malesureng“, sebuah tuntutan bagi pemimpin atau sosok yang dituakan untuk hadir secara nyata, peduli, dan menjadi pemecah masalah (problem solver). Ulama harusnya berada di tengah pasar yang pengap, gang-gang sempit nan becek, atau pematang sawah kering. Bukan malah mengisolasi diri di ketinggian lantai 40.
Kita membayangkan, dari ketinggian itu, rakyat hanya akan terlihat seperti titik-titik kecil yang bergerak, sekecil kelingking, yang mungkin dianggap tidak berarti dalam pengambilan keputusan-keputusan besar. Ada bahaya psikologis di sana; ketinggian seringkali membuat orang lupa pada mereka yang di bawah.
Dalam situasi yang kian geger ini, kita rindu sosok seperti KH. Wahab Hasbullah. Sebagaimana diceritakan Adam Malik, KH. Wahab adalah tipe ulama yang tak segan bermalam di pos ronda atau tidur di surau kecil di pelosok desa. Wibawanya tidak turun hanya karena bajunya terkena debu jalanan; justru pengabdiannya pada orang kecil itulah yang memuliakan namanya di mata sejarah. Inilah jenis ulama yang seharusnya diperkuat posisinya oleh negara. Bukan mereka yang sibuk menanti peresmian gedung mewah di tengah jerit lapar warganya sendiri.
Bagi warga NU, lihatlah Gus Dur. Beliau meneladani sosok Semar, tokoh pewayangan yang sakti tapi memilih hidup sebagai rakyat jelata yang kumal. Di hati Gus Dur hanya ada orang-orang lemah yang harus dibela habis-habisan.
Bagi warga Muhammadiyah, ingatlah pak AR Fachruddin. Beliau juga seorang Semar yang sangat zuhud, hidup bersahaja, dan benar-benar “ngopeni” kaum lemah. Inilah inti kehadiran agama dalam ruang sosial: menjadi perisai bagi yang tertindas, bukan menjadi pajangan di gedung mentereng.
Sangat mungkin, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban yang berat kelak, kita disoal oleh Tuhan, kita terlalu sibuk membangun masjid yang megah, menyelenggarakan pengajian mewah, dan seremonial keagamaan yang gegap gempita setiap hari, ditambah gedung mentereng 40 lantai yang mungkin sedang dinanti-nanti, tapi kita abai pada fakta bahwa ada anak yang meninggal dunia karena tak mampu membeli alat tulis seharga Rp.10.000. Kita membiarkan seorang ibu di Bandung putus asa menghadapi himpitan ekonomi hingga nekat mengakhiri hidup anak-anaknya. Mereka tercekik tanpa ada tangan agama yang merangkulnya. Salah siapa, sehingga agama tidak bekerja di level kesusahan umat itu?
Kita sangat akrab dengan adagium “tasharruf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manutun bi al-maslahah“, kebijakan pemimpin atau pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan umum. Pesan singkat yang seharusnya sekelompok ulama lebih paham tentangnya dan bagaimana membuat adagium itu dapat bekerja. Kita sebetulnya tidak ingin, MUI dibincangkan seolah ia kembali ke “khittah” atau tujuan asal, sebagaimana dulu untuk alat kekuasaan orba. Jauh di masa itu, MUI diyakini didirikan oleh orde baru untuk alat mencengkram para ulama di bawah kekuasaan Soeharto.
Respon ini, kalau lah hendak dibaca baik, barangkali adalah upaya menyentuh nurani sekelompok orang yang berada di MUI. Bahwa agama yang gagal menyelamatkan nyawa seorang anak yang putus asa adalah agama yang sedang kehilangan ruhnya. Dan gedung 40 lantai itu, jika benar-benar berdiri di atas air mata kemiskinan, hanyalah sebuah monumen kesombongan. Ia akan menjadi saksi bisu betapa jauhnya jarak antara meja para ulama dengan piring nasi umatnya yang kosong.
Dan, untuk Prabowo, cobalah tonton film Mission Impossible: The Final Reckoning, di film itu, Ethan Hunt yang diperankan oleh Tom Cruise mengucapkan kalimat yang mungkin cocok untuk diilhami, “being a leader means doing good for those we don’t know“: menjadi pemimpin artinya berbuat baik demi mereka yang tidak kita kenal. Bukan pada siapa yang dikenal.
Penulis: Suriadi
Editor: Andi Surianto