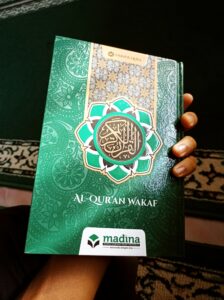Dari Projo ke Partai: Cermin Panjang Loyalitas dan Kekuasaan dalam Sejarah Indonesia

Sejarah sering kali bergerak seperti air yang mengalir: ia tidak pernah benar-benar berulang secara identik, tetapi selalu menemukan bentuk baru dari pola yang lama. Keputusan Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, untuk bergabung ke dalam partai politik pada masa setelah berakhirnya era kepemimpinan Jokowi, adalah salah satu riak dari arus panjang itu. Riak kecil yang, bila ditilik dengan pandangan historis, memantulkan gambaran masa lalu—tentang bagaimana gerakan rakyat, idealisme, dan kekuasaan senantiasa berdialektika di tanah ini sejak masa kolonial.
Ketika Budi Arie pertama kali muncul di panggung nasional sebagai pemimpin gerakan relawan Jokowi, ia mempersonifikasi semangat rakyat kecil yang menaruh harapan kepada seorang pemimpin yang dianggap “dari mereka sendiri”. Projo lahir bukan dari rahim partai, melainkan dari kerinduan terhadap politik yang jujur, sederhana, dan dekat dengan rakyat. Namun waktu berjalan, kekuasaan pun berubah, dan yang semula gerakan moral kini berdiri di ambang pintu politik formal. Dari sini, sejarah seolah berbisik: “ini bukan pertama kalinya yang seperti ini terjadi.”
Lebih dari seabad silam, pada 1908, dr. Soetomo dan Wahidin Sudirohusodo mendirikan Budi Utomo dengan semangat yang hampir sama—membangkitkan martabat bangsa melalui pendidikan, kebudayaan, dan solidaritas sosial. Tidak ada cita-cita politik dalam arti kekuasaan; mereka ingin mencerdaskan, bukan memerintah. Namun sejarah tidak pernah membiarkan idealisme tetap murni. Tekanan kolonial dan desakan zaman memaksa Budi Utomo bergerak dari ruang moral ke gelanggang politik. Para anggotanya terpecah: sebagian tetap ingin menjaga kemurnian perjuangan kebangsaan, sebagian lain memilih masuk ke Volksraad, dewan rakyat bentukan pemerintah kolonial. Di sanalah, untuk pertama kali, moralitas sosial berubah menjadi kalkulasi kekuasaan.
Kisah itu berulang pada dekade berikutnya melalui Sarekat Islam, gerakan ekonomi dan keagamaan yang didirikan Haji Samanhudi dan dipimpin oleh H.O.S. Tjokroaminoto. Pada mulanya, SI berdiri atas dasar keadilan sosial—menentang praktik dagang kolonial dan diskriminasi ekonomi. Tapi seperti diuraikan Takashi Shiraishi dalam An Age in Motion, Sarekat Islam tumbuh menjadi kekuatan politik rakyat yang besar, dengan sayap-sayap ideologis yang saling bertentangan. Di bawah Tjokroaminoto, SI mencoba menjaga idealisme moral Islam dan nasionalisme, namun arus politik membawa mereka ke arah yang lebih keras: sosialisme, komunisme, dan pertentangan internal.
Sejarawan Sartono Kartodirdjo pernah menulis bahwa gerakan sosial seperti SI atau pemberontakan Banten 1888 menunjukkan “dialektika antara kesadaran rakyat dan struktur kekuasaan.” Ketika gerakan rakyat mulai menyentuh wilayah kekuasaan, ia akan diuji—apakah tetap menjadi kekuatan moral atau terserap oleh sistem yang hendak ia ubah. Dalam banyak hal, Projo hari ini sedang menapaki jalan yang sama.
Projo, yang bermula sebagai gerakan spontan relawan Jokowi, berkembang menjadi jaringan nasional yang berpengaruh. Ia lahir dari moralitas politik: keinginan untuk melawan oligarki dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Namun setelah Jokowi berkuasa dua periode, relawan menghadapi dilema klasik: bagaimana tetap menjadi “penjaga moral” ketika kekuasaan yang dulu didukung kini sudah menjadi milik sendiri? Di sinilah langkah Budi Arie memasuki partai menjadi menarik secara historiografis. Ia seperti Tjokroaminoto yang memasuki gelanggang politik untuk menegakkan cita-cita rakyat, tapi juga seperti Soetomo yang perlahan kehilangan kendali atas gerakannya sendiri.
Jika kita membaca Benedict Anderson dalam Language and Power, kekuasaan di Indonesia sering kali lahir dari “simbol-simbol moral yang kemudian dilembagakan.” Jokowi dengan blusukan dan kesederhanaannya menciptakan bahasa moral yang diresapi oleh rakyat. Projo menjadi penjaga bahasa moral itu. Tetapi begitu simbol-simbol itu dilembagakan—melalui struktur partai, jabatan, dan birokrasi—makna moralnya menjadi cair. Loyalitas terhadap pemimpin berubah menjadi loyalitas terhadap sistem. Dan seperti sejarah mengajarkan, setiap sistem selalu memiliki logika kekuasaannya sendiri.
Fenomena Budi Arie tidak dapat dipahami hanya sebagai ambisi pribadi, melainkan sebagai bagian dari siklus historis politik Indonesia. Dari masa kolonial hingga kini, gerakan rakyat selalu berujung pada dilema antara idealisme dan institusionalisasi. Budi Utomo kehilangan jiwanya ketika menjadi elitis; Sarekat Islam terpecah ketika menjadi partai; Projo kini berhadapan dengan risiko yang sama ketika menjadi bagian dari kekuasaan formal. Namun di sisi lain, setiap fase ini juga merupakan langkah menuju kematangan politik bangsa—sebuah proses di mana rakyat belajar bahwa kekuasaan bukan sekadar moralitas, tapi juga kemampuan mengelola struktur.
Sejarawan Vedi R. Hadiz menyebut fenomena seperti ini sebagai oligarchic reproduction—reproduksi kekuasaan di mana gerakan sosial, tanpa disadari, menjadi bagian dari sistem yang dulu mereka kritik. Dalam demokrasi elektoral seperti Indonesia, relawan tidak bisa bertahan lama sebagai kekuatan moral murni; mereka akhirnya harus bernegosiasi dengan kekuasaan jika ingin bertahan. Budi Arie, dalam hal ini, bukan sekadar pengkhianat idealisme relawan, tetapi simbol dari transformasi tak terelakkan: ketika politik rakyat memasuki tahap kedewasaannya.
Namun sejarah juga mengajarkan kehati-hatian. Ketika Tjokroaminoto wafat pada 1934, Sarekat Islam kehilangan arah dan perlahan tenggelam. Begitu pula Budi Utomo yang memudar setelah kehilangan figur-figur penggeraknya. Loyalitas personal yang menjadi fondasi gerakan sering kali tidak cukup untuk menopang keberlanjutan organisasi ketika pemimpin tiada. Di sinilah masa depan Projo dipertaruhkan: apakah ia akan tetap hidup setelah Jokowi tak lagi berkuasa, ataukah akan menjadi catatan kaki dalam sejarah politik relawan Indonesia.
Dalam arus sejarah panjang Indonesia, langkah Budi Arie terasa seperti gema masa lalu yang datang kembali dengan wujud baru. Ia menunjukkan bahwa garis antara idealisme dan kekuasaan, antara gerakan dan partai, antara rakyat dan elite, selalu tipis dan rapuh. Namun dalam pandangan historiografis, langkah itu juga tak terhindarkan. Seperti kata Sartono Kartodirdjo, sejarah bukan hanya perulangan peristiwa, melainkan “dialektika antara struktur dan kesadaran.” Dan mungkin, melalui dialektika inilah bangsa ini terus belajar menyeimbangkan moralitas rakyat dengan realitas kekuasaan negara.
Dari Budi Utomo ke Sarekat Islam, dari Tjokroaminoto ke Budi Arie, garis sejarah itu terus bersambung. Gerakan rakyat yang lahir dari idealisme, ketika bersentuhan dengan kekuasaan, akan berubah bentuk—kadang menjadi lebih kuat, kadang kehilangan arah. Tapi di dalam setiap perubahan itu, terselip pelajaran abadi: bahwa politik adalah cermin karakter bangsa sendiri—kadang jujur, kadang licin, tapi selalu bergerak di antara cita-cita dan kepentingan.
Dan ketika Budi Arie akhirnya memutuskan melangkah ke partai, sejarah seakan tersenyum: sungguh, ini bukan kisah baru. Ini hanyalah bab lanjutan dari roman panjang bangsa yang tak henti mencari keseimbangan antara budi dan kuasa, rakyat dan negara, moral dan realitas.