Pemberontakan Setengah Detik
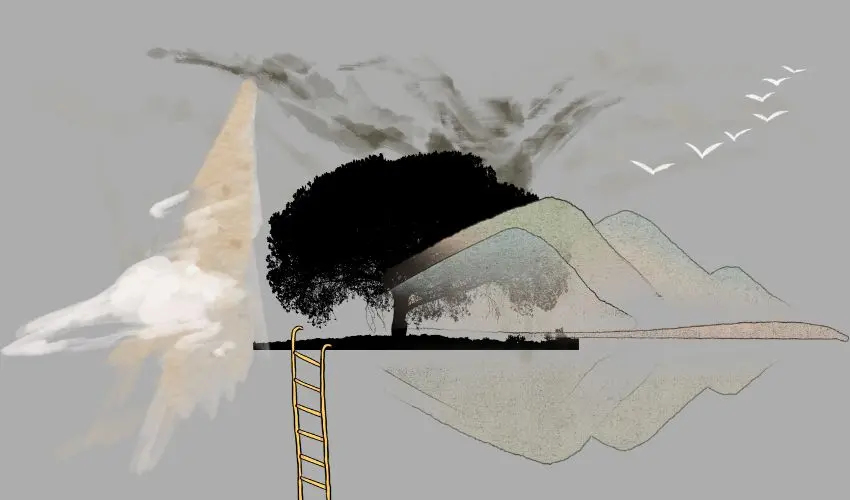
Pagi selalu dimulai dengan kekalahan kecil. Pukul 05.00, alarm ponsel menjerit. Di detik itu, sebelum kesadaran saya pulih sepenuhnya, sebuah tangan bergerak keluar dari balik selimut. Jari telunjuk menekan tombol snooze. Gerakan itu presisi, otomatis, dan tanpa persetujuan “saya”.
Siapa yang memerintahkan tangan itu? Bukan saya. “Saya”—sang kesadaran, sang ego yang merasa memegang kendali—masih terperangkap dalam sisa mimpi yang kabur. Yang menggerakkan tangan itu adalah jutaan tahun evolusi, ditenagai oleh sisa adenosin di otak dan keengganan purba untuk meninggalkan kehangatan gua.
Sepuluh menit kemudian saya bangun bersama rasa bersalah yang sudah menjadi kawan akrab. Dan di tepi tempat tidur sambil menatap debu yang jungkir balik tersorot cahaya jendela pertanyaan-pertanyaan berulang kembali mencekik leher:
“Jika untuk bangun tidur saja kau harus berperang melawan diri sendiri, seberapa besar sebenarnya “kuasa” yang kau miliki atas hidup ini?”
Kita tumbuh besar dengan disuapi dongeng heroik tentang kehendak bebas. Guru-guru, motivator, hingga lirik lagu pop memberitahu bahwa kita adalah “nahkoda bagi jiwa kita sendiri”, bahwa “nasib ada di tangan kita”. Kalimat-kalimat itu terdengar indah, gagah, dan memberdayakan. Tapi mari kita jujur setengah mati, turunkan ego kita ke tanah, dan lihat realitasnya.
Seringkali, kita hanyalah penumpang di dalam sebuah mesin daging yang amat canggih. Tubuh dan otak ini, bukanlah tong kosong yang menunggu diisi air. Mereka adalah perpustakaan bersejarah—sesak dengan naskah kuno yang ditulis oleh nenek moyang yang takut dimangsa harimau. Ia papan sirkuit yang diprogram oleh trauma masa kecil, yang bahkan tidak sanggup kita ingat. Ia budak dari hormon—dopamin yang menuntut kepuasan instan, kortisol yang menciptakan kecemasan tanpa sebab, dan serotonin yang naik-turun seperti ombak laut utara.
Ketika saya marah pada pengendara motor yang memotong jalur saya pagi ini, kemarahan itu sejatinya sangat sia-sia. Ia hanya ledakan yang entah disebabkan oleh apa atau siapa. Amigdala saya—bagian otak yang seukuran kacang almond dan setua reptil—membajak sistem saraf, mengirim darah ke otot, dan mematikan logika, jauh sebelum saya sempat berpikir, “Apakah marah ini berguna?”.
Jadi, di mana letak si “Nahkoda”? Di mana letak kehendak bebas jika setiap pikiran, perasaan, dan impuls muncul sebagai reaksi rantai kimiawi yang tidak saya mulai? Apakah kita hanya boneka biokimia yang berhalusinasi bahwa kita bisa memotong tali kita sendiri?
Tirani Algoritma Bawah Sadar
Mari selami jurang keputusasaan ini sedikit lebih dalam sebelum kita mencari cahaya. Penting bagi kita untuk tidak berpaling dari kekejaman determinisme.
Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah algoritma. Data yang masuk adalah genetik orang tua Anda, lingkungan tempat Anda tumbuh, makanan yang Anda makan, dan setiap trauma atau pujian yang pernah Anda terima. Algoritma itu memproses semuanya di bawah sadar, lalu memuntahkannya menjadi perilaku berupa keputusan.
Seorang pecandu tidak “memilih” untuk menghancurkan hidupnya demi satu suntikan lagi; sirkuit reward system di otaknya telah diretas, memaksanya mengejar dopamin seolah-olah itu oksigen. Seorang yang depresi tidak “memilih” untuk sedih; kimiawi otaknya telah meredupkan lampu-lampu harapan. Bahkan hal sepele seperti memilih menu makan siang seringkali didikte oleh bakteri di usus yang mengirim sinyal ke otak tentang nutrisi apa yang mereka butuhkan.
Gagasan klise bahwa “kita bisa menjadi apa saja yang kita mau” bukan hanya naif, tapi juga kejam. Ia menimpakan beban kesalahan pada individu atas hal-hal yang berada di luar kendali mereka. Ia membuat kita membenci diri sendiri saat kita gagal diet, saat kita gagal bangun pagi, atau saat kita gagal menahan amarah. Kita merasa lemah. Kita merasa cacat moral.
Padahal, kita sedang melawan raksasa.
Kita semua pernah berdiri di depan cermin, menatap mata sendiri, kemudian bertanya: “Jika pikiran berikutnya yang muncul di kepala adalah hasil dari reaksi neuron sebelumnya, maka di mana ‘Aku’? Apakah aku hanyalah penonton yang terjebak di dalam bioskop 4D, merasakan semua sensasinya, tapi tidak memegang remote control?”
Keresahan ini bukan sekadar permainan filsafat di menara gading. Ini adalah darah dan keringat keseharian. Ini adalah alasan mengapa kita mengirim pesan pada mantan kekasih meski tahu itu ide buruk. Ini adalah alasan mengapa kita menunda pekerjaan penting demi menggulir layar ponsel selama dua jam. Kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, tapi ada kekuatan lain—tirani otomatisasi—yang memegang kemudi.
Jika esai ini berakhir di sini, ini akan menjadi tragedi. Sebuah obituari bagi kebebasan manusia. Tapi untungnya, neurosains dan kontemplasi mendalam menyisakan satu pintu darurat. Sebuah celah sempit yang hampir tak terlihat, namun cukup untuk menyelamatkan martabat kita sebagai manusia.
Penemuan Celah Keramat
Pada tahun 1980-an, seorang peneliti bernama Benjamin Libet melakukan eksperimen yang mengguncang dunia filsafat. Ia menemukan bahwa otak kita mempersiapkan gerakan (seperti menggerakkan jari) beberapa milidetik sebelum kita secara sadar merasa ingin menggerakkannya.
Banyak orang menafsirkan ini sebagai bukti bahwa kehendak bebas itu mati. Bahwa otak memutuskan, baru kemudian kesadaran kita diberitahu, seolah-olah kita adalah bos yang hanya diminta tanda tangan di atas keputusan yang sudah dibuat bawahan.
Namun, ada interpretasi lain. Interpretasi yang menjadi landasan pemberontakan saya.
Memang benar, kita tidak punya kuasa atas impuls yang muncul. Pikiran untuk marah, takut, atau menginginkan sesuatu, muncul seperti tamu tak diundang. Kita tidak punya Free Will (Kehendak Bebas untuk memulai). Tapi, penelitian menunjukkan bahwa dalam jeda sepersekian detik antara munculnya impuls dan terjadinya tindakan nyata, kita memiliki kemampuan untuk membatalkannya.
Kita mungkin tidak punya Free Will, tapi kita punya Free Won’t.
Inilah teori yang mengubah segalanya. Kebebasan bukanlah pedang untuk menebas hutan dan menciptakan jalan baru sesuka hati. Kebebasan adalah perisai. Kebebasan adalah rem tangan.
Bayangkan sebuah skenario: Seseorang menghina karya tulis Anda.
Detik 0,0: Telinga mendengar hinaan.
Detik 0,1: Amigdala bereaksi. Darah mendidih.
Detik 0,2: Muncul impuls kuat di otak: “Maki dia! Hancurkan dia!”
Detik 0,3: Mulut Anda mulai terbuka, paru-paru mengambil napas untuk berteriak.
Di sinilah, di detik 0,4 hingga 0,5, keajaiban itu terjadi.
Ada celah sempit. Di celah itu, korteks prefrontal—bagian otak yang paling “manusiawi”—bisa masuk dan berkata: “Tidak.”
Ia tidak bisa menghilangkan rasa marah itu (karena hormon sudah terlanjur lepas). Tapi ia bisa menahan mulut agar tidak mengeluarkan kata-kata racun. Ia bisa memveto perintah eksekusi yang dikirim oleh otak.
Viktor Frankl, seorang psikolog yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, pernah menulis dengan sangat indah tentang hal ini. Dia tidak berbicara tentang neuron, tapi dia berbicara tentang jiwa. Dia berkata, “Di antara stimulus dan respons, ada sebuah ruang. Di dalam ruang itu terdapat kekuatan kita untuk memilih respons. Di dalam respons kita itulah letak pertumbuhan dan kebebasan kita.”
Saya menyebut ruang itu sebagai “Celah Setengah Detik”.
Di sanalah satu-satunya tempat di mana kita menjadi manusia. Di luar celah itu, kita hanyalah binatang cerdas atau mesin yang bisa berhitung. Tapi di dalam celah itu, saat kita menatap hasrat kita sendiri dan berani menentangnya, kita menjadi sesuatu yang lebih luhur.
Menjadi Pemberontak yang “Membumi”
Setelah menyadari hal ini, definisi saya tentang hidup berubah total. Hidup bukan lagi tentang mengejar kebahagiaan atau kesuksesan semata. Hidup adalah serangkaian latihan militer untuk memperlebar “Celah Setengah Detik” itu.
Esai ini harus menjadi seruan perang. Tapi bukan perang dengan pedang dan darah di medan laga, melainkan perang dingin di dalam batok kepala sendiri. Ini adalah esai yang berapi-api karena tidak ada yang lebih panas daripada gesekan antara impuls biologis dan kehendak sadar.
Bagaimana cara kerjanya di dunia nyata?
Mari kita kembali ke hal-hal yang membumi. Mari kita bicara tentang momen ketika Anda pulang kerja, lelah, dan pasangan Anda lupa membuang sampah (lagi).
Impuls pertama (Sang Robot): Berteriak. Mengungkit kesalahan masa lalu. “Kamu selalu begini, tidak pernah menghargaiku!”
Ini adalah naskah lama. Ini adalah klise. Ini adalah jalur neuron yang sudah ditebalkan oleh kebiasaan bertahun-tahun. Melakukan ini terasa enak dan benar sesaat, karena ego kita makan dari sana.
Tindakan Pemberontak (Sang Manusia): Anda merasakan panas di dada. Anda mendengar kalimat makian itu sudah tersusun rapi di lidah. Tapi Anda diam. Anda masuk ke Celah Setengah Detik. Anda menahan napas. Anda melihat impuls itu sebagai objek terpisah—seperti melihat awan hitam lewat—bukan sebagai diri Anda.
Lalu Anda menggunakan Free Won’t. Anda membatalkan ledakan itu. Anda memilih—dengan susah payah, dengan gigi gemeretak—untuk berkata dengan nada datar, “Sayang, tolong sampahnya.”
Itu tidak terlihat heroik dari luar. Tidak ada musik latar orkestra yang megah. Tidak ada tepuk tangan. Anda mungkin masih merasa kesal. Tapi di dalam arsitektur jiwa Anda, baru saja terjadi kemenangan monumental. Anda baru saja mematahkan rantai kausalitas. Anda baru saja menolak menjadi mesin.
Contoh lain: Kecanduan digital.
Ponsel bergetar. Impuls untuk melihat notifikasi begitu kuat, seperti gatal yang harus digaruk. Robot di dalam diri Anda berkata, “Lihatlah, siapa tahu penting.”
Pemberontakan terjadi saat Anda menatap layar yang menyala itu, merasakan tarikan magnetnya, dan dengan sadar membalikkan ponsel itu menghadap ke bawah.
Sakit? Sedikit. Ada rasa tidak nyaman karena dopamin tidak terpenuhi. Tapi rasa sakit itu adalah rasa sakit pertumbuhan. Itu adalah bukti bahwa Anda sedang hidup, bukan sedang diprogram.
Manifesto Kemerdekaan
Maka, inilah kesimpulan yang ingin saya tawarkan—bukan sebagai guru yang berdiri di mimbar, tapi sebagai sesama prajurit yang babak belur di parit pertempuran ini.
Berhentilah berharap untuk memiliki kendali total atas apa yang Anda rasakan atau apa yang Anda pikirkan. Itu adalah harapan palsu yang hanya akan melahirkan kekecewaan. Otak Anda akan terus memproduksi sampah, ketakutan, dan hasrat yang aneh. Biarkan saja. Itu tugasnya.
Tugas Anda, tugas mulia Anda, adalah menjadi Penjaga Gerbang.
Jadilah skeptis terhadap pikiran Anda sendiri. Jangan percaya pada impuls pertama. Impuls pertama adalah tawaran dari masa lalu; respons kedua adalah ciptaan masa depan.
Kehendak bebas bukanlah anugerah yang diberikan Tuhan saat lahir, lengkap dan utuh. Tidak. Kehendak bebas adalah otot. Ia lemah pada awalnya. Jika tidak dilatih, ia akan atropi, dan kita akan menghabiskan sisa hidup sebagai zombie yang berjalan, makan, dan bekerja berdasarkan algoritma lingkungan.
Tapi jika dilatih… Ya Tuhan, jika dilatih, ia menjadi senjata yang menakutkan bagi nasib.
Mari kita menjadi berapi-api dalam ketenangan kita.
Mari kita menjadi garang dalam kemampuan kita untuk menahan diri.
Mari kita merayakan kepahlawanan yang tidak terlihat: pahlawan yang memilih untuk tidak mengirim pesan jahat itu, pahlawan yang memilih untuk bangun saat tubuh ingin tidur, pahlawan yang memilih untuk memaafkan saat dendam terasa lebih manis.
Dunia mungkin melihat kita sebagai manusia biasa yang menjalani rutinitas membosankan. Tapi kita tahu kebenarannya. Di setiap detik yang lewat, di setiap persimpangan sinapsis, kita sedang melakukan kudeta. Kita sedang menggulingkan tirani biologi dan menegakkan bendera kesadaran.
Kita mungkin tidak bisa memilih laut tempat kita berlayar, atau badai yang menghantam. Kita bahkan mungkin tidak bisa memilih desain kapal kita. Tapi demi segala yang suci di semesta ini, tangan kita tidak akan pernah lepas dari kemudi.
Di celah setengah detik itulah, saya ada.
Di celah setengah detik itulah, saya bebas.
Editor: Ihya Ulumuddin









