Menangis Bersama Sumatera
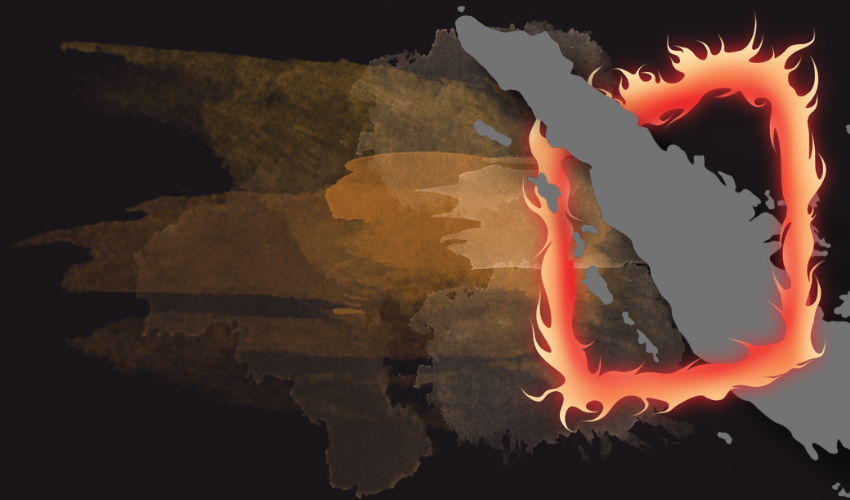
Angka 969 itu bukan sekadar hitungan matematika. Bagi orang-orang yang duduk di kantor pemerintahan di Jakarta, mungkin itu hanya data statistik untuk laporan akhir tahun. Tapi bagi kita, rakyat biasa, angka itu adalah nyawa. Itu adalah seorang ayah yang tak akan pulang makan malam nanti, seorang ibu yang tak bisa lagi memeluk anaknya, dan balita yang masa depannya terhenti di bawah tumpukan lumpur.
Hari ini, Rabu 10 Desember 2025, Sumatera sedang menangis hebat. Dari ujung Aceh, turun ke Sumatera Utara, hingga ke Sumatera Barat, tanah Andalas ini sedang “sakit”. Berita pagi ini mengabarkan korban jiwa akibat banjir dan longsor sudah hampir menyentuh seribu orang. Belum lagi, dini hari tadi saudara kita di Solok dikejutkan oleh guncangan gempa saat sedang tidur lelap.
Sebagai pengamat yang melihat ini dari kacamata sosial, saya tidak ingin berbicara soal lempeng bumi atau curah hujan milimeter per detik. Saya ingin berbicara soal kita. Soal manusia. Soal bagaimana kita hidup bertetangga dengan alam, dan kenapa alam kini seolah “marah” besar kepada kita.
Musibah atau Teguran Keras?
Mari kita jujur pada diri sendiri. Banjir bandang di Aceh Tamiang, longsor parah di Tapanuli Selatan, hingga banjir lahar di Sumatera Barat, apakah ini murni salah hujan yang turun deras?
Hujan adalah berkah Tuhan. Ia menyuburkan tanah, mengisi sumur, dan menghidupkan sawah. Tapi, kenapa berkah itu berubah menjadi musibah pembunuh?
Jawabannya sederhana, namun pahit: Karena kita telah merusak “rumah” bagi air.
Bayangkan hutan-hutan di bukit itu sebagai “payung” dan “spons” raksasa. Dulu, saat hujan deras turun, akar-akar pohon akan memeluk air itu, menyimpannya di dalam tanah, lalu mengalirkannya pelan-pelan ke sungai. Air datang dengan sopan.
Tapi sekarang? Coba lihat bukit-bukit di hulu sungai kita. Banyak yang sudah “botak”. Pohon-pohon raksasa ditebang demi keuntungan segelintir orang—entah untuk tambang, entah untuk kebun sawit yang luasnya sejauh mata memandang. Ketika hutan hilang, air hujan tidak punya tempat bersandar. Ia meluncur deras ke bawah, membawa tanah, batu, dan kayu gelondongan, lalu menghantam rumah-rumah warga miskin yang tak tahu apa-apa di pinggir sungai.
Ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah tragedi sosial akibat keserakahan. Yang menebang pohon di atas gunung mungkin sedang duduk nyaman di kota besar, sementara yang tertimbun longsor di Batang Toru adalah rakyat kecil yang hanya punya rumah petak sederhana. Ada ketidakadilan yang nyata di sini.
Hidup di Atas Tanah yang “Labil”
Belum kering air mata karena banjir, tanah Solok berguncang dini hari tadi. Gempa. Warga panik, lari keluar rumah di tengah malam buta.
Kejadian gempa di Solok dan aktivitas Gunung Marapi yang masih batuk-batuk mengingatkan kita pada satu hal: Kita ini menumpang. Kita menumpang hidup di atas punggung bumi yang aktif bergerak. Sumatera itu indah, tanahnya subur, pemandangannya molek, tapi di bawahnya ada energi besar yang bisa meledak kapan saja.
Secara sosial, ini menciptakan kondisi psikologis yang berat bagi masyarakat kita. Bayangkan perasaan seorang ibu di Sumatera Barat saat ini. Di atas, langit mendung gelap (takut banjir). Di bawah, tanah bergoyang (takut gempa). Di kejauhan, gunung mengepul (takut lahar). Hidup dalam rasa “was-was” yang terus menerus itu sangat melelahkan jiwa.
Dampaknya? Trauma. Anak-anak menjadi takut mendengar suara gemuruh. Orang tua menjadi susah tidur. Kita menghadapi krisis kesehatan mental massal yang seringkali luput dari perhatian pemerintah yang sibuk mengurus bantuan beras dan mie instan. Bantuan makanan itu penting, tapi memulihkan rasa aman di hati warga itu jauh lebih sulit.
Runtuhnya Modal Sosial Kita
Namun, di tengah kegelapan ini, saya melihat secercah cahaya. Cahaya itu bernama Gotong Royong.
Saat jalan di Lembah Anai putus, atau saat desa di Aceh terisolasi, siapa yang pertama kali datang menolong? Tetangga. Pemuda setempat. Komunitas relawan. Sebelum tim SAR berseragam oranye datang, tangan-tangan wargalah yang pertama kali menggali lumpur mencari korban.
Ini membuktikan bahwa “modal sosial” orang Sumatera itu kuat. Rasa persaudaraan (ukhuwah) kita diuji, dan kita lulus ujian itu. Orang Aceh membantu orang Batak, orang Minang mengirim rendang untuk pengungsi. Bencana ini, sekejam apa pun, mengingatkan kita bahwa pada akhirnya kita hanya punya satu sama lain.
Tapi, ada satu penyakit sosial yang harus kita obati: Hobi menyebar Hoaks.
Di tengah kepanikan gempa Solok tadi pagi, atau saat banjir besar kemarin, masih saja ada orang iseng yang menyebar kabar bohong di WhatsApp. “Bendungan jebol!”, “Akan ada tsunami besar!”, “Gunung mau meletus dahsyat!”.
Tolonglah berhenti. Menyebar berita bohong di saat saudara kita sedang ketakutan adalah perbuatan yang sangat jahat. Itu bukan sekadar iseng, itu meneror mental orang yang sedang susah. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Kalau tidak bisa membantu dengan tenaga atau uang, setidaknya bantulah dengan doa dan ketenangan. Jangan memperkeruh air yang sudah keruh.
Apa yang Harus Berubah?
Kita tidak bisa membatalkan hujan. Kita tidak bisa menghentikan gempa. Itu kuasa Tuhan. Tapi kita bisa mengubah nasib kita dengan mengubah perilaku kita.
#1 Berhentilah “Memerkosa” Alam
Pemerintah harus tegas. Jangan lagi kasih izin buka lahan di hutan lindung. Jangan lagi biarkan bukit digunduli. Alam sudah memberi peringatan keras: “Cukup!”. Jika kita terus serakah, Desember tahun depan, dan tahun depannya lagi, kita akan mengangkut jenazah lagi. Mau sampai kapan?
#2 Sadar Bencana Harus Jadi Gaya Hidup
Orang Jepang tahu harus lari ke mana saat gempa karena mereka dilatih sejak TK. Kita? Kita seringkali masih bingung, bahkan malah sibuk merekam video demi konten viral saat air bah datang. Budaya ini harus diubah. Kita harus paham, kalau tinggal di pinggir sungai, saat hujan tak berhenti 2 jam, segeralah mengungsi. Jangan tunggu air masuk rumah. Nyawa lebih berharga dari harta.
#3 Membangun Bukan Asal Jadi
Rumah dan jalan di Sumatera tidak boleh dibangun asal-asalan lagi. Kita hidup di daerah rawan. Membangun rumah di tebing curam tanpa penguat sama saja setor nyawa. Pemerintah daerah harus lebih ketat mengatur di mana warga boleh dan tidak boleh membangun rumah. Ini demi keselamatan warga itu sendiri.
Doa untuk Andalas
Kepada 969 jiwa yang telah pergi mendahului kita, kita tundukkan kepala. Mereka adalah martir yang mengingatkan kita akan kelalaian kita menjaga bumi.
Sumatera hari ini sedang berduka, tapi Sumatera tidak boleh menyerah. Air mata ini harus menjadi penyiram semangat untuk berbenah. Mari kita rawat kembali hutan kita, mari kita bersihkan sungai kita dari sampah, dan mari kita pererat rangkulan tangan antar sesama.
Semoga hujan yang turun esok hari kembali menjadi rahmat, bukan pembawa maut. Dan semoga tanah yang kita pijak memberikan rasa aman, bukan rasa takut.
Kuatlah Aceh. Kuatlah Sumatera Utara. Kuatlah Sumatera Barat. Kita hadapi ini bersama.









