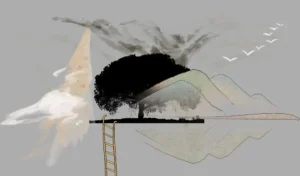Penderitaan yang Disalahkan: Hegemoni, Rasa Malu, dan Kesunyian Subaltern dalam Puisi N. A. Nekrasov dan Realitas Pendidikan Indonesia

Penderitaan sering kali dianggap sebagai pengalaman personal yang lahir dari kelemahan individu, padahal dalam banyak kasus ia merupakan hasil kerja struktur sosial yang begitu dalam sehingga tidak lagi dikenali sebagai penindasan. Sastra, dalam bentuknya yang paling jujur, kerap merekam momen ketika penderitaan tersebut tidak mampu menemukan bahasa sosialnya dan justru berbalik menjadi rasa malu serta kesalahan diri. Puisi karya N. A. Nekrasov merupakan salah satu contoh kuat bagaimana kesedihan personal sesungguhnya menyimpan jejak hegemoni yang bekerja diam-diam dalam kesadaran subjek.
Ketika dari kegelapan menyesatkan
Dengan kata tegas penuh keberanian
Kurenggut jiwa yang jatuh,
Dan menggeliat dalam nestapa,
Kau kutuk cela yang menjeratmu
Dan ketika hatimu terlena, resah
Oleh bara kenangan menyiksa
Kau utarakan kisah
Dari kehidupan lalu sebelum kedatanganku
Dan tiba-tiba kau tutupi wajahmu
Dengan tangan gemetar, menanggung malu
Sarat kengerian, luluh dalam isakan haru,
Marah, dan terguncang
Dst…
— Penggalan puisi karya N. A. Nekrasov
Puisi karya N. A. Nekrasov yang dikutip dalam teks ini, meskipun pada permukaan tampak sebagai penggalan lirikal yang intim dan personal, sesungguhnya bekerja sebagai teks sosial yang sarat muatan ideologis. Ia memperlihatkan bahwa penderitaan manusia tidak hanya hadir sebagai pengalaman psikologis individual, melainkan dibentuk, diarahkan, dan dimediasi oleh struktur sosial yang bekerja melalui kesadaran sehari-hari. Dalam kerangka pemikiran Antonio Gramsci—khususnya melalui konsep hegemoni, common sense, dan subaltern—puisi ini dapat dibaca bukan sekadar sebagai ekspresi kesedihan personal, melainkan sebagai dokumen kesadaran sosial dari subjek yang hidup di bawah dominasi tanpa bahasa perlawanan yang memadai.
Larik pembuka, “Ketika dari kegelapan menyesatkan,” segera menempatkan subjek puisi dalam situasi kehilangan orientasi. Kegelapan di sini tidak hanya menunjuk pada suasana batin yang muram, tetapi juga pada kondisi epistemologis: ketidakmampuan memahami dunia secara jernih dan struktural. Dalam pemikiran Gramsci, kondisi ini berkelindan dengan apa yang ia sebut sebagai common sense, yakni kumpulan gagasan yang terfragmentasi, tidak sistematis, dan diterima begitu saja sebagai kebenaran alamiah. Subjek yang hidup dalam common sense hegemonik tetap mampu merasakan penderitaan, tetapi tidak memiliki perangkat konseptual untuk menautkannya dengan sebab-sebab sosial yang lebih luas. Ia tersesat bukan karena ketiadaan nalar, melainkan karena bernalar dengan kerangka makna yang disediakan oleh tatanan dominan.
Upaya untuk keluar dari kondisi tersebut mulai tampak dalam larik “Dengan kata tegas penuh keberanian.” Bahasa hadir sebagai medium awal artikulasi. Namun keberanian ini, sebagaimana diperlihatkan oleh keseluruhan puisi, masih bersifat individual dan rapuh. Gramsci menegaskan bahwa kesadaran kritis tidak lahir secara spontan dari individu yang terisolasi, melainkan melalui proses panjang artikulasi kolektif. Kata-kata yang diucapkan subjek puisi belum memiliki daya sosial; ia masih bergerak dalam ruang privat yang sempit dan belum mencapai posisi sebagai subjek historis yang terorganisasi.
Kondisi kehancuran batin subjek semakin diperdalam melalui larik “Kurenggut jiwa yang jatuh / Dan menggeliat dalam nestapa.” Jiwa yang jatuh menunjuk pada hilangnya pijakan simbolik dan sosial. Dalam pengertian Gramscian, subjek semacam ini berada pada posisi subaltern: mereka yang hidup di bawah dominasi, tetapi tidak memiliki sarana representasi yang sah. Subaltern tidak hanya mengalami penindasan material, tetapi juga penyingkiran simbolik; pengalaman hidup mereka tidak diakui sebagai pengetahuan sosial yang bernilai. Oleh karena itu, penderitaan mereka tidak pernah benar-benar mencapai penyelesaian, melainkan terus hidup, menggeliat, dan berulang dalam ruang yang sama.
Aspek yang paling menentukan dalam puisi ini adalah arah penderitaan tersebut yang berbalik ke dalam diri subjek. Larik “Kau kutuk cela yang menjeratmu” memperlihatkan dengan sangat jelas mekanisme internalisasi dominasi. Dalam hegemoni yang efektif, kekuasaan tidak perlu hadir dalam bentuk paksaan eksternal yang terus-menerus. Individu belajar menyalahkan dirinya sendiri atas kondisi yang sejatinya bersifat struktural. Gramsci menyebut mekanisme ini sebagai kemenangan ideologis kelompok dominan, yakni ketika yang tertindas turut menjaga tatanan yang menindas mereka melalui rasa bersalah, rasa malu, dan penerimaan nasib.
Kenangan kemudian tampil sebagai kekuatan represif yang tidak kalah kejam dalam larik “Oleh bara kenangan menyiksa.” Masa lalu tidak hadir sebagai sumber refleksi atau pemulihan, melainkan sebagai luka yang terus membakar. Dalam sejarah subaltern, sebagaimana dicatat Gramsci, pengalaman kolektif jarang memperoleh pengakuan institusional dan jarang tercatat dalam narasi resmi. Akibatnya, ingatan tidak pernah diproses secara sosial, melainkan bertahan sebagai trauma individual yang terisolasi, tanpa mekanisme penyembuhan kolektif.
Ketika subjek akhirnya “mengutarakan kisah / Dari kehidupan lalu sebelum kedatanganku,” puisi mencapai momen artikulasi yang krusial. Namun momen ini tidak berujung pada pembebasan. Yang muncul justru reaksi tubuh yang penuh ketakutan: “Dan tiba-tiba kau tutupi wajahmu / Dengan tangan gemetar, menanggung malu.” Rasa malu di sini berfungsi sebagai emosi hegemonik yang paling efektif. Ia bekerja sebagai sensor internal yang mendorong subjek menarik diri dari ruang sosial bahkan sebelum represi eksternal terjadi. Menutupi wajah menjadi simbol penolakan terhadap visibilitas; subjek memandang kisah hidupnya sendiri sebagai sesuatu yang tidak layak untuk dilihat, didengar, atau diakui.
Puisi ini ditutup dengan kondisi emosi yang tercerai-berai: “Sarat kengerian, luluh dalam isakan haru, / Marah, dan terguncang.” Kemarahan hadir, tetapi tidak menemukan bentuk politik. Dalam istilah Gramsci, kesadaran subjek masih berada pada tahap pra-hegemonik: ia merasakan ketidakadilan, tetapi belum mampu mengartikulasikannya sebagai proyek kolektif atau counter-hegemony. Tidak terdapat resolusi atau janji pembebasan. Justru dalam ketiadaan itulah puisi ini memperlihatkan kejujuran historisnya.
Kerangka pembacaan ini menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada realitas sosial kontemporer, khususnya kasus siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang meninggal setelah mengalami tekanan psikologis akibat kemiskinan dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pendidikan. Tragedi ini kerap dipahami secara dangkal sebagai persoalan personal atau kegagalan keluarga. Namun, ketika dibaca melalui lensa Gramsci dan disejajarkan dengan puisi Nekrasov, peristiwa tersebut memperlihatkan mekanisme yang serupa: kerja hegemoni pada tingkat kesadaran paling intim.
Anak tersebut hidup dalam common sense hegemonik, di mana sekolah dipahami sebagai kewajiban moral, keberhasilan akademik sebagai ukuran nilai diri, dan ketidakmampuan memenuhi tuntutan pendidikan sebagai kegagalan personal. Meskipun pendidikan dasar secara formal disebut “gratis”, realitas materialnya tetap menuntut biaya dan kesiapan ekonomi. Ketika negara dan masyarakat tidak menjamin kondisi material tersebut, tetapi tetap menuntut kepatuhan moral, maka beban ideologis itu dialihkan kepada individu, bahkan kepada anak-anak.
Dalam konteks ini, anak tersebut menempati posisi subaltern dalam pengertian Gramscian yang paling literal. Ia tidak memiliki perangkat simbolik maupun ruang artikulasi untuk memahami penderitaannya sebagai persoalan struktural. Ia tidak memiliki representasi sosial yang melindungi pengalamannya. Yang tersisa hanyalah rasa gagal dan rasa malu. Di titik inilah larik “Kau kutuk cela yang menjeratmu” menemukan manifestasi nyatanya: bukan sistem pendidikan, ketimpangan regional, atau kemiskinan struktural yang dikutuk, melainkan diri sendiri.
Rasa malu yang digambarkan dalam puisi—“Dengan tangan gemetar, menanggung malu”—juga hadir secara laten dalam kasus ini: malu untuk meminta, malu untuk tidak mampu, dan malu untuk tertinggal. Dalam common sense hegemonik, rasa malu diproduksi sebagai emosi moral yang seolah mendidik, padahal sesungguhnya berfungsi sebagai alat disiplin sosial yang sangat efektif. Anak tersebut tidak memberontak; ia justru berupaya patuh pada tuntutan moral yang mustahil ia penuhi.
Kasus ini juga memperlihatkan absennya counter-hegemony. Tidak terdapat intervensi sosial yang menjangkau kesadaran anak sebelum tragedi terjadi. Negara baru hadir setelah kematian, dalam bentuk belasungkawa dan janji evaluasi. Hal ini sejalan dengan analisis Gramsci bahwa hegemoni sering kali baru dipertanyakan setelah krisis mencapai titik paling fatal. Seperti halnya puisi Nekrasov, tragedi ini tidak menawarkan resolusi, melainkan meninggalkan keguncangan.
Dengan menggabungkan pembacaan puisi Nekrasov dan realitas sosial di Nusa Tenggara Timur melalui kerangka Gramsci, dapat ditarik kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan: penderitaan yang tampak personal dan individual sering kali merupakan hasil dari struktur hegemonik yang bekerja melalui common sense, rasa malu, dan internalisasi kesalahan. Baik dalam teks sastra abad ke-19 maupun dalam konteks Indonesia kontemporer, subaltern mengalami penderitaan bukan hanya karena kemiskinan atau ketidakadilan material, tetapi karena ketiadaan bahasa sosial yang memungkinkan mereka memahami dan menantang kondisi tersebut.
Puisi Nekrasov, dengan demikian, tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga berfungsi sebagai cermin kritis bagi realitas masa kini. Ia menunjukkan bahwa sebelum muncul perlawanan terbuka, selalu ada fase sunyi di mana penderitaan diinternalisasi dan dimaknai sebagai nasib. Kasus siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur memperlihatkan konsekuensi ekstrem dari fase sunyi tersebut ketika dialami oleh subjek yang paling rentan.
Secara Gramscian, tugas intelektual dan sosial bukan sekadar meratapi tragedi, melainkan membongkar common sense yang memungkinkan tragedi itu terjadi. Selama kemiskinan dipahami sebagai kegagalan personal, selama pendidikan diposisikan sebagai kewajiban moral tanpa jaminan material, dan selama suara subaltern—terutama anak-anak—tidak memperoleh ruang artikulasi, maka tragedi serupa akan terus mungkin terjadi. Dengan demikian, pembacaan kritis terhadap sastra dan realitas sosial bukan hanya relevan, melainkan mendesak sebagai bagian dari tanggung jawab intelektual dan kemanusiaan.
Puisi Nekrasov memperlihatkan bahwa sebelum ketidakadilan tampil sebagai perlawanan terbuka, ia terlebih dahulu hidup sebagai kesunyian yang dipendam, rasa malu yang disembunyikan, dan kemarahan yang tidak menemukan bahasa. Kasus siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa mekanisme yang sama masih bekerja hingga hari ini, bahkan terhadap subjek yang paling rentan. Dengan membaca sastra melalui kerangka Gramsci dan mengaitkannya dengan realitas sosial, esai ini menegaskan bahwa tugas intelektual bukan sekadar memahami penderitaan, melainkan membongkar common sense yang membuat penderitaan itu tampak wajar dan tak terelakkan. Selama penderitaan terus disalahkan kepada individu, suara subaltern akan tetap terbungkam, dan tragedi akan terus berulang dalam bentuk yang berbeda, tetapi dengan logika yang sama.